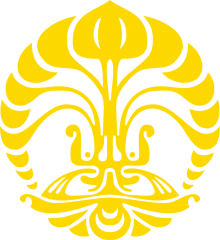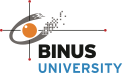September biasanya menandai dimulainya tahun ajaran baru di universitas-universitas di Jalur Gaza. Namun, puluhan ribu mahasiswa pendidikan tinggi tidak dapat melanjutkan studi mereka karena genosida Israel yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Meski di tengah situasi genting, sejumlah inisiatif muncul agar mahasiswa bisa terus mengejar gelar mereka.
Sejak pengeboman Israel pada 7 Oktober 2024 lalu, terjadi kerusakan pada sistem pendidikan Gaza terjadi di semua tingkatan. Hampir 93% bangunan sekolah telah rusak atau hancur, dan sejumlah besar telah diubah menjadi tempat penampungan untuk menampung 1,9 juta orang (sekitar 90% dari populasi) yang telah mengungsi dari rumah mereka.
Sampai pertengahan September tahun ini, lebih dari 10.000 anak usia sekolah dan lebih dari 400 staf pendidikan telah tewas dalam operasi Israel. Terkait universitas, ke-12 universitas di Gaza telah rusak parah atau hancur total. Lebih dari 650 mahasiswa tewas serta lebih dari 110 staf pengajar, menurut Kementerian Pendidikan Palestina dilansir dari The New Humanitarian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saida Affouneh, dekan fakultas pendidikan di Universitas An-Najah di Tepi Barat, membantu meluncurkan Prakarsa Dukungan Pendidikan Teknis (TESI) yang bertujuan untuk menyediakan akses bagi mahasiswa di Gaza ke kursus daring berbayar untuk melanjutkan studi mereka.
Pembelajaran Daring di Tengah Genosida
TESI dan universitas-universitas di Gaza berkolaborasi untuk menyediakan staf pengajar bagi para profesor dan pakar dari seluruh dunia. Lebih dari 3.500 profesor dan mahasiswa pascasarjana telah mendaftar untuk mengajar berbagai kursus mulai dari ilmu komputer dan kedokteran hewan hingga penerjemahan sastra dan hukum perdata internasional.
Affouneh, yang memiliki gelar doktor dalam pendidikan darurat dan mengkhususkan diri dalam pembelajaran daring, mengatakan hampir 50.000 mahasiswa telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan inisiatif tersebut.
Meskipun mendapat tanggapan yang luar biasa, inisiatif tersebut hanya mampu menerima 3.000 mahasiswa selama fase pertamanya. Sedikit lebih dari separuhnya mampu menyelesaikan semester musim semi. Dari mereka yang tidak menyelesaikannya, banyak yang studinya terganggu oleh pengungsian berulang kali dan kurangnya akses internet.
Mahasiswa Kedokteran Jadi Fokus Utama
Saat ini, menemukan cara bagi mahasiswa kedokteran untuk melanjutkan pendidikan mereka telah menjadi prioritas yang sangat mendesak. Seperti universitas lainnya, pengajaran di dua perguruan tinggi kedokteran di Gaza, Universitas Al-Azhar dan Universitas Islam Gaza, dihentikan setelah 7 Oktober. Dua universitas tersebut hancur selama minggu-minggu awal perang.
Namun para siswa menyadari bahwa keterampilan mereka sangat dibutuhkan. Para mahasiswa turut membantu sistem medis Gaza yang diserang kewalahan dalam menghadapi beban pasien yang sangat besar.
Salah satu mahasiswa tersebut adalah Tareq Abdel Jawwad, 23 tahun, mahasiswa kedokteran tahun kelima di Al-Azhar. Karena kuliah dan rotasi klinisnya dibatalkan, Jawwad mulai menjadi relawan di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Gaza tengah. Dia akan bekerja selama tiga hingga empat hari di rumah sakit sebelum menempuh perjalanan berbahaya pulang untuk tidur.
"Rumah sakit itu penuh dengan pasien di lantai. Saya tidak punya tempat untuk tidur," katanya dikutip Jumat (27/9/2024).
Jawwad, yang sekarang berada di luar Gaza, bekerja lebih dari 800 jam dalam 90 hari sebagai relawan rumah sakit. Luka-luka perang dan tubuh orang-orang yang terbunuh dalam serangan udara Israel sangat mengerikan.
"Ini bisa jadi traumatis.Tidak semua mahasiswa siap menghadapi ini," katanya.
Jawwad kini memimpin komite keterlibatan mahasiswa dalam sebuah inisiatif bernama Gaza Educate Medics, yang membantu mahasiswa kedokteran Gaza melanjutkan pendidikan mereka. Skema ini diluncurkan pada bulan Juni dengan dukungan dari para dekan fakultas kedokteran dari Al-Azhar dan Universitas Islam.
Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa memenuhi persyaratan gelar dengan menyediakan pengajaran medis daring dan penempatan klinis di rumah sakit di Gaza atau di luar Palestina.
Perjuangan Dosen
Majd al-Kurd, seorang dosen Bahasa Inggris di Universitas Islam, mengisi daya ponselnya di rumah tetangga dan membayar sekitar $1 atau Rp 17 ribu per jam untuk mengakses hotspot seluler, praktik yang menurutnya umum di Gaza utara, tempat mereka yang memiliki akses internet menyediakan layanan dengan membayar.
Tarifnya sekitar empat kali lipat dari biaya internet sehari sebelum perang dan sangat mahal bagi populasi yang sebagian besar terpaksa menganggur akibat perang.
Namun, al-Kurd membayarnya agar ia dapat terus berbagi kuliah dan berkomunikasi dengan para mahasiswanya melalui platform pendidikan Moodle dan Facebook. Melanjutkan mengajar, katanya, adalah tugas yang dengan bangga ia lakukan secara cuma-cuma.
"Generasi orang yang buta huruf adalah hal terakhir yang ingin kami lihat di sini, di Gaza," ujarnya.
"Universitas tempat saya bekerja hancur total, dan bahkan pusat [pengajaran bahasa Inggris kecil] tempat saya bekerja dibakar," sambungnya.
(nir/faz)