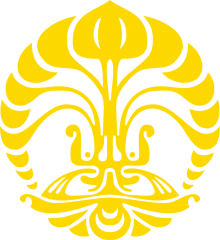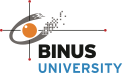Hampir 10 bulan pengeboman Israel terjadi di Palestina. Sekolah-sekolah telah hancur atau diubah menjadi tempat pengungsian. Lantas, bagaimana nasib para siswa?
Tercatat, terdapat 630.000 siswa di Palestina berhenti sekolah karena pengeboman. Mereka tidak masuk sekolah karena harus mengungsi dari satu tempat ke tempat lainnya.
Kementerian Pendidikan Palestina menyebut pada Selasa (21/8/2024) lalu jika 186 sekolah di Gaza telah rusak parah atau hancur total. Kendati demikian, kementerian memutuskan jika kelas-kelas akan dilanjutkan dari tenda-tenda dan melalui pendidikan daring.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dengan genosida yang masih berlanjut, Salama Marouf selaku juru bicara kantor media pemerintah di Gaza mengatakan mustahil untuk membuat rencana tersebut.
"Saat ini tidak mungkin untuk membahas rencana apapun dari otoritas pendidikan di Gaza karena tidak ada kapasitas untuk mengadakan pertemuan atau berkonsultasi mengenai rinciannya," katanya dalam The National.
Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) yang mengelola sekolah-sekolah di jalur itu, mengatakan tidak berencana untuk membuka pendidikan formal.
"Kami tidak memiliki pembaruan baru mengenai dimulainya tahun ajaran dan kami baru memulai, sejak tanggal 1 Agustus, kegiatan hiburan bagi siswa sebagai pendidikan nonformal," kata juru bicara lembaga itu, Inas Hamdan.
Orang Tua Khawatir akan Dampak Genosida pada Anak
Orang tua salah satu murid seperti Rasha Yahya, 31, lebih khawatir dengan dampak genosida terhadap anak-anak mereka.
"Ini bukan hanya tentang mereka yang kehilangan pendidikan. Anak-anak di Gaza telah kehilangan ketenangan pikiran, semua kenangan, permainan, dan kehidupan mereka yang nyaman," kata Yahya, yang memiliki seorang putri berusia 7 tahun.
Yahya mengatakan dia sulit membayangkan keadaan untuk kembali seperti sebelum perang.
"Anak-anak membutuhkan program besar-besaran, yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan UNRWA, untuk membantu mereka mendapatkan kembali sebagian kehidupan mereka sebelum perang dan berintegrasi kembali ke dalam proses pendidikan seperti sebelum dimulai," katanya.
Melihat dampak kekerasan terhadap anaknya, Yahya menyarankan agar tahun ajaran berikutnya diisi dengan kegiatan dan permainan yang mendukung kondisi psikologis anak-anak. Pembelajaran tatap muka, katanya, juga lebih penting.
"Saya juga menentang pendidikan daring, meskipun internet dan listrik tersedia. Karena tidak akan pernah seperti pendidikan tatap muka, yang dapat meningkatkan perilaku anak dan memperbaiki kebiasaan serta ide buruk yang mereka peroleh selama perang," tambahnya.
Orang tua anak lainnya, Haneen Abu Zer, 28 tahun, percaya akan keputusan untuk memulai pendidikan penting bagi kedua anaknya yang masih duduk di taman kanak-kanak dan kelas satu. Namun, ia tidak merasa anak-anaknya siap untuk mulai belajar.
"Saya mencoba mengajari putri saya cara menulis dan membaca. Tetapi saya gagal karena ia masih duduk di kelas satu dan tahap pendidikan ini membutuhkan spesialis," katanya.
(nir/nwy)