Salah satu wabah penyakit yang cukup banyak ditemukan di Cirebon pada masa Hindia Belanda adalah tuberkulosis (TBC). Kasus TBC di Cirebon bahkan pernah diberitakan dalam beberapa artikel surat kabar Hindia Belanda, seperti yang terbit dalam surat kabar De Locomotif edisi 12 April 1938.
Laporan dari dokter Hindia Belanda kepada Stichting Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose (SCVT), sebuah lembaga swasta pada masa itu yang fokus menangani penyakit TBC, menyebutkan bahwa jumlah pasien dengan masalah kesehatan saluran pernapasan di Cirebon meningkat drastis.
Pada triwulan ketiga, yakni pada bulan Oktober, tercatat sekitar 800 orang pasien yang mengalami gejala TBC, 530 di antaranya adalah pasien lanjut usia. Di bulan Desember, jumlahnya bertambah sekitar 270 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedangkan pada Desember 270 orang mendaftar berobat, di antaranya ditemukan 26 dahak positif TBC dalam satu kali pemeriksaan. Tiga pasien dikirim ke Patjet dan Tjisaroea, sedangkan 8 laki-laki dan 5 perempuan penderita tuberkulosis dirawat di Rumah Sakit Kota "Oranje", tulis surat kabar De Locomotif edisi 12 April 1938.
Tidak hanya yang memiliki gejala TBC yang dites, tetapi untuk mencegah penyebaran lebih luas, anak-anak sekolah di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon juga ikut diuji. Selain itu, dilakukan juga kunjungan secara intensif oleh para dokter ke rumah pasien TBC. Namun, selama kunjungan tersebut, banyak ditemukan pasien TBC yang hidup dalam kondisi serba kekurangan.
"Kunjungan rumah tersebut dilakukan secara intensif dan sistematis dan selama periode pelaporan telah dilakukan kunjungan ke rumah pasien sebanyak 371 orang. Selama kunjungan rumah pasien tersebut, berulang kali ternyata ada beban finansial. Dari situ diperoleh komitmen bahwa, dalam kasus tertentu, bantuan keuangan akan diberikan jika diperlukan dan memungkinkan," tulis surat kabar Lokomotif edisi 12 April 1938.
Surat kabar De Indische Courant edisi 14 Februari 1936 juga menyebutkan penyebab maraknya penyakit TBC di Hindia Belanda, seperti pola hidup tidak sehat dan kekurangan gizi yang dialami penduduk. Untuk mengatasinya, Dienst der Volksgezondheid (DVG) atau Lembaga Kesehatan Hindia Belanda menyarankan pembentukan dapur umum di beberapa daerah, termasuk Cirebon.
"Laporan resmi DVG, tidak diragukan lagi mengenai hal ini, dan penyebaran penyakit masyarakat seperti malaria, TBC dan beri-beri juga dapat dikaitkan dengan kekurangan gizi yang dialami penduduk di berbagai kabupaten," tulis surat kabar De Indische Courant edisi 14 Februari 1936.
 Ilustrasi Cirebon masa Hindia Belanda Foto: Arsip KITLV perpustakaan Leiden University Ilustrasi Cirebon masa Hindia Belanda Foto: Arsip KITLV perpustakaan Leiden University |
Selain menjangkiti masyarakat umum, TBC juga banyak menyerang narapidana di penjara Cirebon. Meskipun tidak disebutkan berapa jumlah narapidana yang meninggal akibat TBC, namun pada tahun 1932 tercatat peningkatan angka kematian narapidana di Lapas Cirebon, seperti yang diberitakan dalam surat kabar Batavia Nieuwsblad edisi 16 November 1932.
"Angka kematian penduduk penjara di Cheribon menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama sembilan bulan pertama tahun 1932," tulis surat kabar Batavia Nieuwsblad edisi 16 November 1932.
Salah satu penyebab tingginya angka kematian adalah buruknya kondisi pabrik tekstil yang ada di penjara. Suasana pabrik tersebut terkontaminasi oleh partikel debu dan serat yang berbahaya, memperburuk kondisi bagi narapidana yang sudah memiliki gejala TBC. Sebagai respons, Lembaga Kesehatan Hindia Belanda menyarankan agar narapidana yang menunjukkan gejala TBC tidak lagi dipaksa bekerja di pabrik tekstil tersebut.
Pembangunan Sanitarium Sidawangi
Karena jumlah pasien yang terus meningkat dan fasilitas kesehatan yang terbatas, pemerintah Hindia Belanda membangun sanatorium khusus untuk penderita TBC yang sedang menjalani pengobatan. Bersama dengan SCVT, banyak kota di Hindia Belanda yang membangun sanatorium, termasuk di Cirebon.
Mengutip surat kabar Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indische edisi 23 November 1939, disebutkan sebuah sanatorium dibangun di Karesidenan Cirebon, tepatnya di dataran tinggi Sidawangi. Lokasi ini dipilih karena memiliki pemandangan pegunungan dan lautan, serta dekat dengan area pertanian dan pemukiman.
"Sanatorium Sidawangi, yang namanya secara harfiah berarti "menjadi harum", yang harus dimaknai secara metaforis sebagai sebuah karya yang dapat menghasilkan lebih banyak manfaat, selanjutnya ,dapat menjadi contoh cemerlang dari efektivitas kerja lokal, untuk merangsang dan membangkitkan kekuatan untuk bekerja sama secara aktif untuk meringankan penderitaan," tulis surat kabar Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indische edisi 23 November 1939.
Dalam surat kabar De Locomotif edisi 22 November 1939, disebutkan tentang syarat pembangunan sanatorium . Menurut pengurus utama SCVT, Dr De Wolf, dalam sambutannya saat peresmian Sanitarium Sidawangi mengatakan, bahwa pembangunan sanatorium harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya sanatorium tidak boleh memberikan kesan yang suram dan tertutup. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, setiap kamar pasien ditempatkan dalam sebuah paviliun sehingga semua pasien dapat menikmati suasana alam bebas, yang jauh dari kesan suram.
"Yang terpenting adalah sanatorium tidak boleh memberikan kesan suram atau tertutup. Keceriaan dan semangat hidup diberikan kepada pasien yang harus tinggal di lingkungan ini, setidaknya selama enam bulan dan bahkan saat mereka di tempat tidur. Itulah sebabnya sistem yang berbeda diterapkan di paviliun dibandingkan di bangsal rumah sakit biasa dengan tempat tidur dua baris. Hanya ada deretan pasien di paviliun ini, sehingga semua orang yang sakit selalu dapat menikmati alam bebas," tulis surat kabar De Locomotif edisi 22 November 1939.
Sanatorium Sidawangi, yang pada awalnya memiliki kapasitas 56 orang pasien, kini telah berkembang menjadi Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Pangeran Kejaksaan, Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
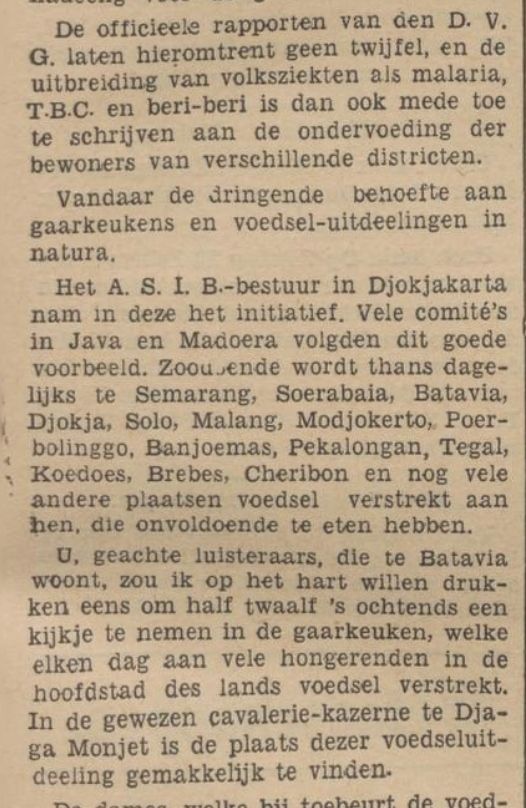 De Indische Courant edisi 14 Februari 1936 Foto: Arsip Delper De Indische Courant edisi 14 Februari 1936 Foto: Arsip Delper |



























































