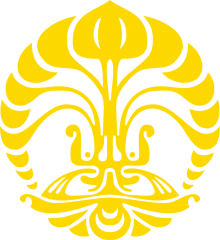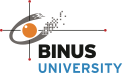Inflasi tak lagi terbatas pada ranah ekonomi. Di dunia akademik, gejala serupa tengah menjadi perhatian yaitu inflasi IPK. Fenomena ini merujuk pada meningkatnya rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan perguruan tinggi dari tahun ke tahun, namun tak sejalan dengan peningkatan kualitas maupun daya saing lulusan di dunia kerja.
Tren ini menuai kritik dari kalangan akademisi, termasuk Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Prof Dr Tuti Budirahayu, Dra, MSi. Ia menilai persoalan ini berakar pada sistem kapitalisme dalam pendidikan tinggi.
Kapitalisme pendidikan terjadi ketika perguruan tinggi dituntut mengikuti logika pasar yakni menerima sebanyak mungkin mahasiswa dan meluluskan sebanyak mungkin pula.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dikatakan kapitalisme pendidikan itu karena sekarang perguruan tinggi itu dituntut, dipaksa untuk bisa memenuhi tuntutan pasar. Artinya harus bisa menerima sebanyak-banyaknya mahasiswa dan meluluskan sebanyak-banyaknya mahasiswa," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikEdu.
Tekanan pasar membuat institusi pendidikan tinggi lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas. Akibatnya, IPK tinggi tak selalu mencerminkan kompetensi lulusan yang mumpuni di lapangan.
Tak hanya tuntutan pasar, sistem akreditasi perguruan tinggi juga dinilai turut menyumbang terjadinya inflasi IPK. Menurut Tuti, kampus cenderung memberikan nilai tinggi demi menjaga status akreditasi institusinya. Kampus berpotensi mengalami penurunan akreditasi apabila banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai rendah.
Selain itu, nilai yang rendah juga mampu menyebabkan sulitnya lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. "Kalau mereka lulus dengan nilai pas-pasan mereka tidak bisa masuk di pasar kerja. Tidak gampang, karena kan sekarang kalau mau menyeleksi karyawan, menyeleksi lulusan perguruan tinggi yang mau bekerja, tentu saja pertama-tama dilihat IPK. Terus yang kedua ya perguruan tingginya dari mana," ujarnya.
Namun, bagi Prof Tuti, IPK sejatinya adalah 'saringan pertama' dalam menilai kualitas seorang lulusan. Tentu, selain IPK tinggi, lulusan juga harapannya memiliki kompetensi yang mumpuni. "Kualitas mahasiswa itu tidak diukur dari IPK saja kan sebetulnya. Nah, bisa dilihat dari aktivitas dia dalam kegiatan kemahasiswaan, organisasi, atau yang sekarang pakai SKP (Sistem Kredit Prestasi)," tegasnya.
Penilaian Alternatif
Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Prof Tuti percaya bahwa ada alternatif lain dalam menilai kualitas lulusan selain dari IPK. "Saya bilang harus ada pembobotan. Ke depan, sistem penilaian itu pembobotan antara IPK dengan aktivitas dan kreativitas dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menunjukkan performa seseorang itu secara utuh. Tentu saja sesuai dengan fakultasnya masing-masing," sebutnya.
Prof Tuti juga mengungkapkan persoalan inflasi IPK bisa berlangsung secara alamiah. Ia meyakini bahwa setiap dosen memegang teguh nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Ia percaya dosen mampu menilai mahasiswa berdasarkan integritas yang ada. Maka, ia berharap mahasiswa turut mampu menunjukkan kapabilitas yang mencerminkan nilai IPK-nya.
"Banyak penilaian yang bisa kita gunakan untuk mengukur kapabilitas dan kemampuan mahasiswa. Saya percaya itu, tidak satu parameter, tidak satu ukuran saja. Banyak ukuran yang bisa dipakai untuk menunjukkan kualitas mahasiswa. Nah, mahasiswa harus menunjukkan itu," ujarnya.
(pal/nwk)