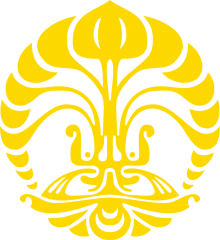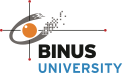Agus Hasan Hidayat dikenal sebagai aktivis disabilitas yang memperjuangkan hak-hak kelompok disabilitas psikososial hingga ke forum internasional. Ia mewakili Transforming Communities for Inclusion (TCI) di komite pemuda Aliansi Disabilitas Internasional.
Disabilitas psikososial adalah ragam disabilitas pada orang yang mengalami gangguan dalam proses berpikir, berperasaan (emosi), berperilaku, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkannya berperan, berpartisipasi penuh, dan efektif berdasarkan kesamaan hak sebagai manusia.
Disabilitas psikososial mencakup gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan kepribadian, seperti dikutip dari Mengenal Anak dengan Disabiltas Psikososial: Panduan Dasar untuk Orang Tua dan Keluarga karya Agus dan rekan-rekan penelitinya, bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2018.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota komite country leadership di Global Mental Health Peer Network ini juga bicara soal disabilitas dan kepemudaan di Conference of The State Parties dan berdialog dengan Deputy Secretary General Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Dua tahun belakangan, pria kelahiran 1991 ini mengembangkan organisasi disabilitas psikososial Remisi yang berfokus pada program dukungan berbasis komunitas. Di sana, ia memperjuangkan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial bersama rekan-rekannya.
Bagaimana kisah Agus terjun ke isu disabilitas psikososial dan kesehatan mental sejak mahasiswa?
Isu Kesehatan Mental di Bangku Kuliah
Agus menuturkan, ia semula mengenal lebih jauh isu kesehatan mental ketika duduk di bangku kuliah. Saat itu, ia sempat mengalami kecemasan yang turut disadari teman dan pengajarnya.
Dari situ, ia pun memberanikan diri bertukar cerita dengan teman yang seorang mahasiswa psikologi. Di satu titik, temannya menyarankan untuk berkonsultasi dengan psikiater sehingga bisa mendapat farmakoterapi untuk depresinya.
Agus kemudian menyadari bahwa teman-teman di sekitarnya juga mengalami berbagai tekanan kuliah dan keluarga, quarter life crisis, hingga masalah kesehatan mental. Bagi Agus, Isu ini kemudian memantik panggilan hatinya untuk bergerak.
"Berangkat dari pengalaman sendiri, saya bergabung menjadi volunteer di organisasi kesehatan mental," tuturnya pada detikEdu.
Menjadi relawan juga membuka kesempatan baginya untuk mengikuti pelatihan terkait kesehatan mental dan disabilitas mental psikososial lebih lanjut, termasuk pelatihan lintas isu seperti buruh dan gender.
Menjadi Relawan
Terjun ke dunia kerelawanan di bidang kesehatan mental, Agus kemudian mempelajari bahwa orang dengan gangguan mental termasuk ke dalam ragam disabilitas mental psikososial yang diakui Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
Tidak hanya diakui ragamnya secara internasional, sambungnya, ia juga lalu mempelajari bahwa orang dengan ragam disabilitas mental psikososial juga punya hak akomodasi layak di lingkungan kerja dan dunia pendidikan. Hak ini juga diakui dalam perundang-undangan Indonesia terkait disabilitas.
"Untuk teman-teman disabilitas mental psikososial yang sudah terdiagnosis, ketika alami masalah di ujian, ada adjusment yang perlu diberikan right away (langsung) oleh penyelenggara pendidikan," kata Agus.
"Ketahui bahwa kita punya reasonable accomodation di dunia pendidikan, seperti tambahan waktu ujian, format tulisan diganti presentasi: fleksibilitas yang disesuaikan dengan kondisi psikologis. Jika tidak diakomodasi, penyelenggara pendidikan bisa dikenai sanksi administrasi," kata Agus.
Ia menuturkan, aturan terkait hak disabilitas mental psikososial sebagai invincible disability masih menghadapi tantangan baik dari pelajar sendiri maupun warga penyelenggara pendidikannya.
Sebab, identifikasi orang dengan ragam disabilitas ini tak bisa secara kasat mata seperti halnya orang dengan disabilitas fisik.
Lebih lanjut, perlu SOP di institusi pendidikan, training bagi guru dan dosen, hingga pemerintah daerah yang seharusnya memiliki unit untuk mengakomodasi pelatihan terkait hak dan kebutuhan warga disabilitas mental psikososial.
Harapannya, siswa dan mahasiswa tidak takut mendapat stigma saat meminta hak seperti cuti karena kondisi dan diagnosis kesehatan mentalnya. Lebih lanjut, mahasiswa juga tak terpikir drop out dan jadi tak percaya akan kemampuannya di masa depan.
"Fungsi guru bimbingan dan konseling (BK), layanan konselor, apakah ada dan berjalan sebagai tempat mahasiswa dan pelajar mengadu? Jika guru BK malah ditakuti, makan pesannya jadi tidak tersampaikan. Seharusnya, ia jadi salah satu tempat ternyaman ceritakan masalah sekolah maupun rumah. Dengan begitu, peserta didik jadi tidak malu dan takut meminta hak dia untuk menyelesaikan pendidikan" tuturnya.
"Fatalnya, orang yang alami depresi 2-3 bulan, pengen keluar kampus jika dibiarkan. Men-DO-kan anak ini berisiko memicu dia merasa nggak bisa jadi apa-apa karena pernah di-DO. Tapi jika diakomodasi sesuai haknya, hingga skripsi, dia bisa berkontribusi besar di masyarakat. Pemahaman ini yang belum banyak dipahami di duniai pendidikan sehingga harus diperjuangkan," imbuh Agus.
Agus menuturkan, implementasi kebijakan oleh negara dan penghapusan aturan yang diskriminatif bagi disabilitas mental psikososial ini perlu terus dikawal.
"Agar lebih aware lagi, bahwa kondisi dan hak ini tidak hanya dilihat dari perspektif medis saja, tetapi juga hak asasi manusia dalam bekerja hingga mengakses pendidikan," tuturnya.
Agus menjelaskan, isu kesehatan mental perlu mulai dilihat dengan pendekatan HAM di samping kesehatan, sebagaimana ada hak atas pekerjaan, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesamaan di hadapan hukum.
Harapannya, tidak ada lagi anggapan bahwa orang dengan disabilitas mental psikososial tidak cakap hukum atau bukan subjek hukum karena tidak sama waras seperti manusia seutuhnya.
"Itu satu dari segudang hak yang dimiliki, untuk dilihat sebagai subjek pembangunan juga, karena selama ini dilihat dari perspektif charity. Padahal, tentunya kami ingin kontribusi juga secara sosial, memajukan bangsa dan berdampak ke masyarakat," imbuh Agus.
Kelompok Dukungan Sebaya
Sehari-hari, Agus aktif di program peer support group atau kelompok dukungan sebaya untuk orang-orang yang mengalami masalah mental. Semula, dukungan sebaya ini dikembangkan di Yayasan Bipolar Care Indonesia khusus untuk orang yang didiagnosis mengalami gangguan bipolar.
"Awalnya banyak temen muda yang dateng, kuliah, terutama SMA, juga ada pekerja muda. Ada juga yang tua dan lansia, tetapi lebih jarang," kata Agus.
"Dari kelompok dukungan sebaya, akhirnya saya dapat gambaran masalah yang teman-teman alami. Dari keluhan awal soal soal stigma dan akses ke layanan kesehatan, muncul masalah-masalah lain yang ternyata juga termasuk diskriminasi sistematis," imbuhnya.
Ia mencontohkan, seseorang dengan disabilitas mental psikososial harus sembunyi-sembunyi minum obat saat bekerja hingga kehilangan kerja dengan dipecat setelah konsumsi obat (farmakoterapi) karena adanya stigma bahwa orang dengan gangguan jiwa dianggap membahayakan atau dianggap tidak layak di berkarya di ranah profesional.
Padahal, adanya upaya seperti pemberian 'ruang tenang' dan penyesuaian atau adjustment lainnya memungkinkan orang disabilitas mental psikososial maupun nondisabilitas jadi berkesempatan menikmati kerja dan belajar untuk menjaga wellbeing-nya.
Temuan ini kemudian diadvokasi Agus dan rekan-rekannya ke kementerian, lembaga dalam negeri, dan konvensi internasional.
"Hal-hal itu kami dokumentasikan dan buat laporannya ke komite CRPD, bagaimana kondisi teman-teman di komunitas, yang masih tinggal dengan keluarga, sendiri, maupun kunjungan ke panti rehabilitasi punya dinas sosial atau milik masyarakat dengan pendekatan rehab berbeda," kata Agus.
Ia menuturkan, temuan masalah di lapangan juga mencakup kerentanan atas kekerasan fisik dan seksual, perawatan paksa atau institusionalisasi, diusir dari keluarga, hingga berakhir di panti, dengan terkena tindakan merendahkan, keji, dan tidak manusiawi (inhumane degrading treatment).
"Tahun ini, kami juga merespons isu konvensi internasional hak sipil politik.. Masih puluhan ribu orang ditahan di detention center, panti serupa penjara yang dilegalkan di UU, yang keberhasilan fungsi resosialisasinya perlu dipertanyakan agar orang dengan disabilitas mental psikososial bisa hidup setara dengan yang tidak disabilitas, berkontribusi pada masyarakat, dan hidup inklusif di masyarakat," jelasnya.
"Bersama rekan-rekan di organisasi sebelumnya, kami dirikan Yayasan Remisi. Kami membuat laporan dan rekomendasi agar CRPD bikin general comment terkait hak atas pekerjaan, lalu agar negara dapat mengimplementasikan deinstitusionalisasi, khususnya dari kacamata disabilitas mental psikososial, khususnya di Indonesia, global south, yang beda dengan di negara maju," sambung Agus.
Di Remisi, Agus dan teman-teman juga membuat sejumlah kelompok dukungan sebaya, spesifiknya buat orang-orang yang mengalami kekerasan seksual. Modulnya disusun bersama psikolog dan penyintas sebagai dokumen yang terus tumbuh, disesuaikan dengan budaya dan kondisi dari waktu ke waktu.
"Jika tertarik, yuk duduk bareng, apa yang teman bisa bantu, nggak harus full time. Apa pun, kontribusi sekecil apapun: desain, menulis. Di sini butuh bantuan untuk gerakan ini sampai ke kampus A, B, C, situasi A, B, C, industri A, B, C; bantu menjelaskan seperti apa nge-treat teman-teman disabilitas mental psikososial, itu penting juga," kata Agus.
"Sebab, setiap jenjang pendidikan, kota, pekerjaan, berbeda-beda tekanannya. Di industri kreatif, yang tekanannya tinggi, masalahnya beda. Teman-teman juga bisa dan butuh speak up. Menulis juga bagian advokasi nonlitigasi untuk membangun ke masyarakat umum, agar gerakan ini didengar dan menjadi gerakan mainstream, layaknya isu buruh dan lingkungan," pungkasnya.
(twu/nwk)