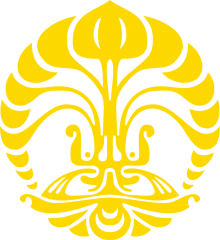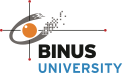Media sosial menjadi platform dengan beragam informasi yang mengalir paling cepat dan termasif tanpa adanya verifikasi kebenaran. Hal ini membuat banyak berita palsu atau hoaks, berkeliaran bebas.
Data yang dilaporkan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2023, menunjukkan ada 1.615 konten di Indonesia yang menyangkut isu hoaks di platform digital dan situs internet. Jumlah ini bisa lebih banyak karena tak semua dilaporkan dan ditangani.
Sayangnya, masih banyak temuan bahwa alih-alih menyaring informasi dengan tepat, penyebaran hoaks justru terus dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas kenapa orang mudah percaya hoaks dan menyebarkannya?
Orang yang Menyebarkan Hoaks Tidak Memiliki Keterampilan Berpikir Kritis
Sebuah studi yang terbit di Proceedings of the National Academy of Sciences, menemukan bahwa orang yang mudah termakan berita palsu dan menyebarkannya, berkaitan dengan cara berpikir.
Studi yang dipimpin University of Southern California (USC) mengungkapkan bahwa hoaks bisa menyebar karena pengguna tidak memiliki keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu.
Selain itu, kemampuan berpikir dan penilaian mereka juga biasanya cenderung dipengaruhi oleh keyakinan politik tertentu yang kuat.
"15% dari orang-orang yang paling sering membagikan berita dalam penelitian ini bertanggung jawab menyebarkan sekitar 30% hingga 40% berita palsu," tulis studi yang dikutip dari situs resmi USC.
Kebiasaan untuk Terus Berkomentar, Mengunggah, dan Membagi Informasi
Terkait mengapa banyak orang mudah menyebarkan berita hoaks, tim peneliti dari USC Marshall School of Business dan USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, terus mendalaminya.
Hasilnya, mereka menemukan bahwa apa yang dilakukan orang-orang saat menyebarkan hoaks berkaitan dengan kebiasaan atau dorongan yang muncul selama bermain media sosial.
Selama ini, tanpa sadar, orang-orang yang bermain media sosial telah kecanduan untuk melakukan like atau menerimanya, berkomentar, mengikuti tren atau isu yang viral, dan menyebarkannya.
"Karena sistem pembelajaran berbasis penghargaan di media sosial, pengguna membentuk kebiasaan berbagi informasi yang mendapat pengakuan dari orang lain," tulis para peneliti.
"Setelah kebiasaan terbentuk, berbagi informasi secara otomatis diaktifkan berdasarkan isyarat di platform tanpa pengguna mempertimbangkan hasil respons yang penting, seperti menyebarkan informasi yang salah," tambah mereka.
Jadi bisa dikatakan, mengunggah, berbagi, dan berinteraksi dengan orang lain di media sosial dapat menjadi suatu kebiasaan.
Ini yang kemudian banyak orang mudah percaya dan menyebarkan berita palsu atau hoaks. Mereka tidak merespons dengan berpikir atau mempertimbangkan, tetapi langsung berkomentar atau menyebarkan karena sudah terbiasa.
"Kebiasaan pengguna media sosial adalah pendorong penyebaran misinformasi yang lebih besar dibandingkan atribut individu. Kami mengetahui dari penelitian sebelumnya bahwa sebagian orang tidak memproses informasi secara kritis, dan sebagian lainnya membentuk opini berdasarkan bias politik, yang juga memengaruhi kemampuan mereka untuk mengenali berita palsu secara online," ujar Gizem Ceylan, pemimpin penelitian di USC Marshall, yang kini menjadi peneliti pascadoktoral di Yale School of Management.
"Kami menunjukkan bahwa struktur penghargaan di platform media sosial memainkan peran yang lebih besar dalam penyebaran misinformasi," imbuhnya.
Penyebaran Hoaks Bisa Sangat Masif
Dalam penelitian yang melibatkan 2.476 pengguna aktif Facebook berusia antara 18 hingga 89 tahun ini, para peneliti menemukan bahwa kebiasaan pengguna media sosial meningkat dua kali lipat.
Bahkan dalam beberapa kasus, jumlah berita palsu yang mereka bagikan menjadi tiga kali lipat. Kebiasaan mereka dalam menyebarkan berita palsu lebih berpengaruh dibandingkan faktor lainnya, termasuk keyakinan politik dan kurangnya penalaran kritis.
Pengguna rutin akan meneruskan berita palsu enam kali lebih banyak dibandingkan pengguna sesekali atau pengguna baru.
"Memahami dinamika di balik penyebaran misinformasi adalah hal yang penting mengingat konsekuensi politik, kesehatan, dan sosialnya," tutur Ian A. Anderson, seorang ilmuwan perilaku dan kandidat doktor di USC Dornsife.
(faz/pal)