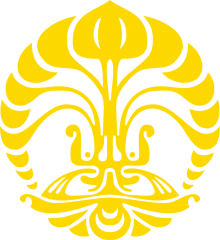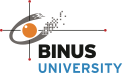Manusia kini mulai beralih ke chatbot AI generatif untuk mengurangi kesepian. Namun, cara ini dinilai justru menimbulkan masalah pada kemampuan berempati.
Pandangan ini disampaikan sosiolog Massachusetts Institute of Technology (MIT) AS, Sherry Turkle di Harvard Law School baru-baru ini, melansir The Harvard Gazette.
Turkle mengaku tidak menampik potensi kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan, penelitian medis, bisnis, hingga seni. Namun, ia menyorot risiko penerapan AI pada proses manusia mempelajari skill hubungan antarmanusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalah Ngobrol ke Manusia
Psikoterapis ini menjelaskan, penelitiannya mendapati banyak orang kini memilih chat (pesan teks) atau media sosial ketimbang interaksi tatap muka. Kecenderungan ini berangkat salah satunya dari ketakutan manusia akan penolakan dan yang akan terjadi.
Dengan berkirim teks, orang-orang merasa tidak terlalu rapuh di depan orang lain. Ini yang menjadikan platform komunikasi digital populer untuk mengobrol dengan keluarga dan teman, kandidat pacar, atau teman curhat.
"Mereka bilang, 'Orang-orang mengecewakan. Mereka menghakimi kita, meninggalkan kita. Drama hubungan antarmanusia sangat melelahkan'," katanya.
"Hubungan kami dengan chatbot adalah suatu hal yang pasti. Chatbot selalu ada siang dan malam," imbuhnya.
Komunikasi Tatap Muka, Penting?
Di sisi lain, Turkle mengingatkan komunikasi tatap muka merupakan faktor penting dalam mengasah kemampuan manusia berempati dan menghargai nilai sebuah hubungan antarpribadi.
Komunikasi dengan manusia secara langsung juga memicu kedekatan dan rasa saling berempati antarpribadi, serta memantik produktivitas dan kerja sama di dunia kerja.
"Percakapan tatap muka adalah tempat berkembangnya kedekatan dan empati," katanya.
"Dan di tempat kerja, percakapan menumbuhkan produktivitas, keterlibatan, serta kejelasan dan kolaborasi," imbuhnya.
Dilema Plus-Minus AI Chatbot buat Curhat
Turkle mengakui big data yang digunakan untuk mengembangkan AI dapat membuat AI chatbot dan terapis AI memberikan rasa terkoneksi. Namun, kata-kata berempati dari AI diberikan oleh mesin, sehingga tidak punya rasa empati sungguhan.
Ia menjelaskan, AI chatbot dan terapis AI dirancang untuk membuat pengguna tetap bahagia lewat kalimat-kalimat berempati. Ini artinya, alat AI ini tidak benar-benar peduli tentang apa yang dialami pengguna.
Kendati demikian, penelitiannya mendapati banyak orang merasa empati bohongan dari AI ternyata cukup memuaskan. Temuan ini selaras dengan pandangan praktisi teknologi AI generatif, bahwa teknologi berbasis big data lebih unggul dalam memberikan kepuasan ketimbang manusia pakar atau terlatih.
Kurang Terapis Psikologi
Di sisi lain, Turkle menjelaskan big data mungkin menghasilkan respons rata-rata yang berlaku untuk kebanyakan orang saja, bukan yang terpersonalisasi sesuai kondisi psikologi manusia yang berbeda-beda di lapangan.
Kondisi ini yang menurutnya menjadikan terapis psikologi AI tidak bisa benar-benar menggantikan psikoterapis manusia sungguhan.
Ia mengamini bahwa institusi penyedia layanan psikologi kekurangan tenaga psikoterapis, terlebih dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Untuk itu, berbagai layanan psikologi kini memanfaatkan AI chatbot terapis sebagai tenaga garda pertama untuk merespons klien.
Namum, Turkle menegaskan bahwa yang dapat mengubah manusia secara jangka panjang adalah hubungan antarpribadi yang terbina, bukan info-info terkurasi yang disampaikan terapis atau AI chatbot terapis semata. Untuk itu, hubungan antarpribadi tatap muka menurutnya tetap jadi kunci.
"Teknologi menantang kita untuk menegaskan diri kita sendiri dan nilai-nilai kemanusiaan kita. Ini artinya, kita harus mencari tahu nilai-nilai yang dimiliki manusia, kendati tidak mudah. Saya pikir pembicaraan soal ini harus dimulai sekarang. Ini benar-benar momen perubahan," pungkasnya.
(twu/faz)