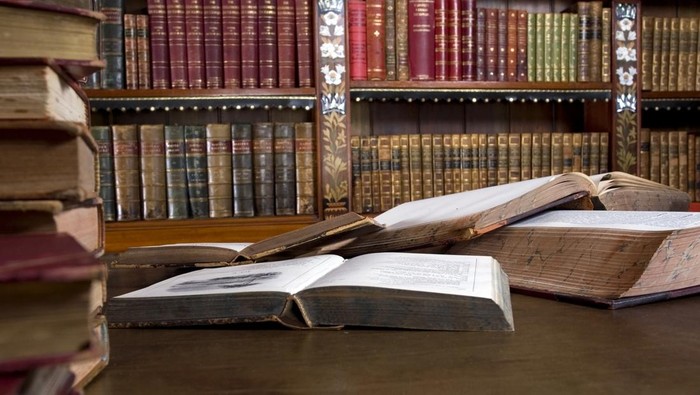Sejarah kesusastraan Sunda dapat ditarik jauh ke zaman kerajaan di mana sastra dikembangkan dalam tradisi lisan yang dominan. Tulisan-tulisan sastra juga masih dalam media daun lontar.
Pada zaman dahulu, kesusastraan terikat pada kisah-kisah kahiangan atau kisah para putra raja. Misalnya dalam jenis-jenis Carita Pantun. Isi carita pantun nyaris selalu tentang raja atau anak-anak raja. Carita pantun Lutung Kasarung isinya berkelindan antara makhluk kahiangan dan makhluk buana panca tengah atau bumi.
Lutung Kasarung adalah Sanghyang Guruminda, anak Sunan Ambu di Kahiangan yang dikutuk menjadi monyet dan harus melakukan penebusan dosa di dunia. Dia kemudian menikah dengan perempuan anak seorang raja Pasir Batang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zaman berubah, manusia Sunda kemudian bersentuhan dengan mesin cetak, dengan kertas, dan produk kesusastraan barat yang 'prosaik' yang dibawa penjajah Belanda. Di samping itu, ada sekelumit anak-anak kaum menak yang diberi kesempatan bersekolah di lembaga berkurikulum barat.
Menurut Yeni Mulyani Supriatin dalam studi berjudul Baruang Ka Nu Ngarora: Representasi Perubahan Sosial Masyarakat Sunda Abad XIX, dijelaskan bahwa salah satu yang menikmati pendidikan formal ala barat itu adalah Daeng Kanduruan Ardiwinata atau namanya sering disingkat D.K. Ardiwinata.
"Untuk itulah, pemerintah kolonial memperkenalkan pendidikan formal pada masyarakat setempat teristimewa pada para menak 'bangsawan' Sunda, termasuk di dalamnya D.K Ardiwinata," tulis Yeni.
D.K. Ardiwinata, aktivis pergerakan sekaligus pendiri komunitas besar Paguyuban Pasundan adalah penulis novel berjudul 'Baruang Ka Nu Ngarora'. Novel ini disebut-sebut sebagai novel modern pertama dalam bahasa Sunda.
Yang menjadi pembeda jelas antara 'Baruang Ka Nu Ngarora' dengan sastra Sunda lama, selain dalam bentuknya yang prosa, juga tema yang diangkat di dalamnya. 'Baruang Ka Nu Ngarora' lebih realistis menceritakan keadaan masyarakat dan dengan latar tempat yang 'nyata', tidak mengawang-awang di kahiangan.
Ceritanya jelas, bahwa masyarakat kecil dipinggirkan secara kultural oleh para menak. Harkat rakyat kecil atau dalam bahasa D.K. Ardiwinata sebagai 'cacah kuricakan' nyaris tidak ada, karena secara ekonomi, cacah kuricakan sangat lemah.
Ingin lebih jelas tentang 'Baruang Ka Nu Ngarora'? Simak sampai tuntas artikel ini yuk!
Waktu Terbit Novel 'Baruang Ka Nu Ngarora'
Studi oleh Yeni Mulyani Supriatin menyebutkan novel 'Baruang Ka Nu Ngarora' yang berarti 'Racun Bagi Remaja' karya D.K. Ardiwinata itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1914.
Penerbitnya adalah G. Kolff & Co di Weltevreden. Novel Sunda ini diterbitkan dalam dua jilid. Jilid pertama setebal 63 halaman dan jilid kedua 48 halaman.
Dalam menulis sinopsis novel tersebut di bawah ini, penulis menggunakan 'Baruang Ka Nu Ngarora' yang diterbitkan ulang oleh Kiblat Buku Utama (2020), dengan tebal 107 halaman.
Sinopsis 'Baruang Ka Nu Ngarora'
'Baruang Ka Nu Ngarora' atau Racun Bagi Remaja berkisah tentang Nyi Rapiah yang menikah dengan pemuda bernama Ujang Kusen. Dalam pernikahan adat Sunda yang tidak selesai dalam sehari, gangguan kesetiaan datang kepada Nyi Rapiah.
Yaitu, menjelang hari-hari pernikahan datang seorang tukang kain Nyi Dampi, yang di samping berdagang ke rumah Nyi Rapiah, juga menitipkan sebuah cincin dari seorang pemuda anak bupati, namanya Aom Usman.
Sambil menitipkan cincin itu, Nyi Dampi memperlihatkan potret Aom Usman yang membuat Nyi Rapiah goyah dalam perjodohannya dengan Ujang Kusen. Bukan hanya goyah karena ternyata Aom Usman juga ganteng, namun karena kepastian keberlimpahan harta Aom Usman.
Tetapi, Nyi Rapiah menolaknya dengan halus titipan Nyi Dampi itu. Dia kemudian tetap menikah dengan Ujang Kusen, meski dalam hatinya teringat terus akan sosok Aom Usman.
Tak Terbiasa Sengsara
Nyi Rapiah si cantik jelita adalah anak Haji Abdul Raup dan merupakan warga Kampung Pasar. Cerita tentangya terjadi pada tahun 1874 di mana Haji Abdul Raup adalah orang kaya kampung, meski tidak kaya-kaya betul seperti keluarga bupati.
Demikian Ujang Kusen, anak Haji Samsudin, juga tidak sengsara-sengsara betul, dan karenanya, dia harus bekerja lebih keras agar bisa hidup mandiri, tidak bergantung kepada kekayaan orang tuanya.
Sebagai pengantin baru, terpikir juga oleh Ujang Kusen untuk merintis usaha. Dia memilih untuk menjadi juragan kopi di daerah yang dekat gunung, juga untuk menjual pakaian dan barang lainnya secara kredit ke warga kampung. Mereka pun memutuskan pindah.
Kepindahan itu, juga untuk menghindari Aom Usman yang setelah diperhatikan, tak hentinya melayangkan godaan kepada Nyi Rapiah yang telah sah menjadi istri Ujang Kusen.
Di gunung, Nyi Rapiah yang tak terbiasa bekerja berat, harus bekerja turun naik gunung untuk memperhatikan orang-orang memanen kopi. Selain capai, juga tidak ada penghiburan lain bagi Nyi Rapiah. Jika biasanya matanya diamnjakan oleh pemandangan gedung-gedung atau rumah yang megah dengan halaman yang bersih, maka di kampung gunung dia tinggal di rumah gubuk dengan halaman becek dan tai kotok di mana-mana.
Kondisi itu membuat Nyi Rapiah tidak betah. Gayung bersambut, ketika dia minta izin tidak ikut ke gunung, datang Si Abdullah, panglayar (mak comblang) antara dia dengan Aom Usman datang ke gubugnya.
Kedatangan itu memang suruhan Aom Usman dan akhirnya, Rapiah yang tidak tahan dengan kehidupan bersama Ujang Kusen memutuskan kabur.
Meminta Cerai dari Ujang Kusen
Peritiwa kaburnya Nyi Rapiah dari rumah Ujang Kusen membuat Ujang Kusen bingung dan mencari-cari. Tapi nyatanya, Nyi Rapiah senang dengan kaburnya itu sebab dia sebelum pulang ke rumah orang tuanya, bisa berjumpa dengan Aom Usman di sebuah rumah gulang-gulang yang bekerja kepada keluarga Aom Usman.
Nyi Rapiah keesokan harinya tiba di rumah orang tuanya, Haji Abdul Raup dan semua keluarganya bertanya ada apa. Diceritakanlah bahwa dia tidak bertah dibawa sengsara oleh Ujang Kusen.
Hubungan pernikahan Nyi Rapiah dan Ujang Kusen akhirnya mengambang. Statusnya masih suami istri tetapi sudah tidak akur dan tidak tinggal bersama.
Hingga suatu hari, Aom Usman memihta seorang preman untuk mendatangi rumah Haji Samsudin, ayah Ujang Kusen untuk meminta kejelasan perceraian Ujang Kusen dengan Nyi Rapiah.
Maksudnya, Nyi Rapiah mau dinikahi oleh Aom Usman, maka Ujang Kusen harus segera menceraikannya. Jika Aom Usman tidak diberikan apa yang dia minta, maka 'perceraian' yang diharapkan itu, biarlah dibeli.
Mendengar 'dibeli', Haji Samsudin marah dan meminta Ujang Kusen segera menulis pernyataan talaknya kepada Nyi Rapiah. Surat itu kemudian dibawa preman tadi dan diserahkan kepada Aom Usman yang kemudian setelah habis masa 'iddah, Nyi Rapiah menikah dengan Aom Usman.
Ujang Kusen Jadi Kriminal
Ujang Kusen yang sakit hati dikhianati cintanya oleh Nyi Rapiah. Bahwa jelas-jelas Nyi Rapiah kabur darinya dan menciptakan alasan agar bisa bercerai darinya dan menikah dengan anak bupati, Aom Usman, kemudian menjadi beringas.
Dia menjadi kriminal sejati, meski yang dirampok adalah harta orang tuanya sendiri. Harta itu dipakai untuk judi, melacur, dan kriminalitas lainnya. Hingga akhirnya Ujang Kusen terpergok sedang beraksi maling duit bapaknya dari brangkas, yang membuatnya masuk penjara.
Tidak Setara Menak-Cacah
Ayah-ibu Aom Usman tidak setuju dengan pernikahan Aom kepada Nyi Rapiah. Meski molek, Nyi Rapiah tetap dianggap sebagai golongan rendah karena bukan dari kalangan bupati atau wedana. Tidak setara derajatnya antara menak dan cacah. Kaum bangsawan dan rakyat biasa.
Karenanya, Aom Usman diminta lagi menikah dengan orang yang sekufu. Ayahnya sudah menyiapkan calon istirnya, yaitu Agang Sariningrat anak Wadana Anu. Aom Usman tak punya pilihan, dia harus menikah lagi.
Nyi Rapiah, 'janda' yang tadinya menjadi kesukaan Aom Usman, lambat laun tergantikan dengan kehadiran Agan Sariningrat yang perawan. Rumah besar yang ditinggali Nyi Rapiah pun dijadikan tempat tinggal Aom Usman dan Agan Sariningrat, sementara Nyi Rapiah dibuatkan rumah baru yang kecil.
Dalam hal dimadu, Nyi Rapiah akhirnya tidak punya kekuatan apapun. Dia hanya tunduk kepada kemauan suaminya itu. Tidak banyak pilihan bagi perempuan Sunda abad ke-19 sebagaimana tergambar dalam novel ini.
(iqk/iqk)