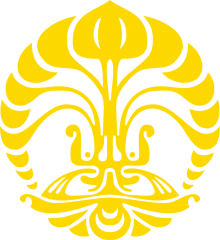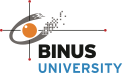Tak sedikit masyarakat yang menyorot kerusakan ekologis sebagai bagian dari penyebab bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Namun, tentu tak lengkap jika pembahasan ini tidak melibatkan analisis kalangan akademisi.
Salah satu yang ikut bersuara adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Mohammad Adib, Drs MA.
Pemaknaan Bencana Perlu Direvisi
Prof Adib menerangkan, dari perspektif antropologi ekologi, apa yang disebut sebagai bencana alam sebenarnya adalah bencana antropogenik, yaitu bencana yang dipicu perilaku manusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, masyarakat perlu merevisi cara memaknai bencana. Pasalnya, banjir; longsor; hingga kekeringan ekstrem tidak lahir dari alam yang marah, tetapi cara manusia mengelola ruang hidupnya.
Ia menegaskan alam tidak sedang marah, melainkan sedang merespons tekanan fisik yang diberikan manusia kepadanya.
"Hujan adalah siklus alam, tetapi banjir adalah bukti kegagalan sistem sosial dan budaya kita dalam merespons siklus tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita telah melampaui daya dukung lingkungan (carrying capacity)," jelasnya, dikutip dari Unair pada Kamis (4/12/2025).
Pembangunan Kerap Berpihak pada Kepentingan Jangka Pendek
Prof Adib juga menyorot krisis tata kelola ruang yang menurutnya bagian penting dari persoalan hari ini.
Ia menilai pembangunan kerap lebih berpihak pada kepentingan manusia jangka pendek. Sayangnya dalam proses ini, hak-hak ekologis yang semestinya dimiliki alam, malah terabaikan.
Ruang yang harusnya menjadi tempat bumi bernapas, misalnya daerah resapan air, bantaran sungai, sampai hutan kota perlahan menjadi kawasan terbangun.
Dampak Kerusakan Dirasakan Masyarakat Kecil, Bukan Pengambil Kebijakan
Pakar antropologi ekologi dan kehutanan sosial ini juga menyebut dampak kerusakan seringnya tidak dirasakan pengambil kebijakan, tetapi justru masyarakat kecil yang terpinggirkan ke zona-zona rawan bencana.
"Ironisnya, dampak dari kerusakan ini seringkali tidak dirasakan oleh pengambil kebijakan, melainkan oleh masyarakat kecil yang terpinggirkan ke zona-zona rawan bencana. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekologis," jelasnya.
Mitigasi Bencana Tak Cukup Pembangunan Fisik
Prof Adib juga mengatakan perubahan nilai budaya ikut memperlebar krisis relasi manusia dengan alam. Ia memandang masyarakat tradisional dahulu memandang alam sebagai mitra hidup. Maka dari itu, timbul kearifan lokal seperti pamali dan hutan larangan yang menjaga keseimbangan lingkungan.
Sayangnya, pola hidup modern yang berorientasi pada kepemilikan mendorong manusia menempatkan alam sebagai objek eksploitasi.
Ia menyebut akar masalah semua ini adalah pergeseran ontologis atau cara pandang manusia modern terhadap alam. Budaya konsumerisme menyebabkan manusia terus mengeruk sumber daya alam tanpa memberi waktu baginya untuk memulihkan diri.
Oleh sebab itu, Prof Adib menegaskan mitigasi bencana tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik saja, tetapi juga perubahan cara pandang yang jauh lebih mendasar. Ia menekankan perlu ada revolusi mental ekologis yang mengembalikan etika kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menghidupkan lagi nilai-nilai lokal dalam kebijakan tata kota modern.
Bencana Bukan Takdir yang Tak Dapat Diubah
Pakar kehutanan sosial ini menuturkan, negara sebagai regulator mempunyai tanggung jawab utama dalam mengarahkan pembangunan yang lebih adaptif terhadap lingkungan. Meski begitu, menurutnya hingga kini belum ada peta jalan pembangunan lingkungan yang jelas dan berjangka panjang. Oleh sebab itu, kebijakan di berbagai sektor kerap berjalan sporadis.
"Tanpa arah yang tegas dari pemerintah, upaya menjaga keseimbangan lingkungan hanya akan bergerak di tempat," ujarnya.
Ia menekanan, bencana bukan takdir yang tidak bisa diubah. Ia menilai, bencana merupakan produk sosial dari cara hidup dan kebijakan yang melampaui batas daya dukung ekologis.
Prof Adib mengajak semua pihak kembali membangun relasi yang lebih selaras dengan alam.
"Kita harus bergerak dari relasi eksploitatif menuju relasi adaptif yang menghargai kearifan lokal sebagai pertahanan ekologis terbaik. Ini adalah panggilan dari nilai budaya," ucapnya.
(nah/twu)