Perjalanan pembangunan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh sederet tokoh nasional dari berbagai daerah, tak terkecuali dari wilayah timur Indonesia tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Di antara sekian banyak pejuang dan tokoh nasional dari wilayah ini, ada 4 figur fenomenal yang sama-sama bernama Jusuf/Yusuf (adanya penyesuaian ejaan dalam sumber-red).
Tokoh-tokoh hebat itu adalah Jenderal M Jusuf, Bacharuddin Jusuf Habibie, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan Jusuf Kalla. Keempat figur Jusuf ini telah memberikan sumbangsih dan pengaruh besar dalam bidang keahliannya masing-masing, mulai dari militer, keagamaan, teknologi dan pendidikan, hingga bisnis dan politik.
Selain kesamaan nama, 4 figur Jusuf ini punya satu kesamaan lain yang memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup dan kesuksesan mereka. Keempatnya sama-sama memegang teguh filosofi hidup dan prinsip Bugis-Makassar dalam langkah perjuangannya. Prinsip Bugis-Makassar ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman kepemimpinan, pendidikan, sampai penyebaran Islam di Nusantara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan berpegang pada filosofi Bugis-Makassar, keempat figur Jusuf berhasil mencapai puncak karier dan menjadi sosok inspiratif bagi generasi penerus Bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, detikers diajak menyelami filosofi dan karakter Bugis-Makassar dari 4 figur Jusuf asal Sulsel.
Syekh Yusuf Al-Makassari, Pejuang Kemerdekaan yang Raih 2 Gelar Pahlawan Nasional
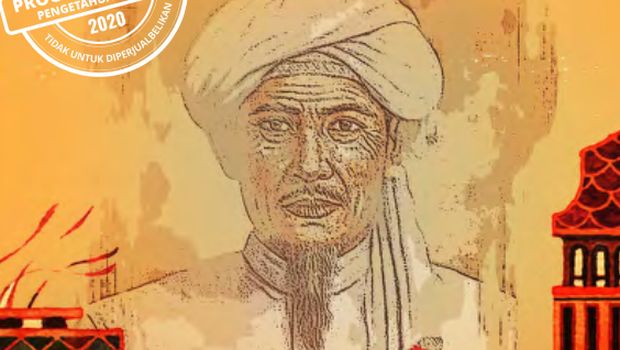 Syekh Yusuf Foto: Buku Tusalama' oleh Labbiri, S.Pd., M.Pd Syekh Yusuf Foto: Buku Tusalama' oleh Labbiri, S.Pd., M.Pd |
Syekh Yusuf juga merupakan tokoh nasional yang berasal dari kalangan bangsawan Makassar, Gowa, dan Tallo. Beliau dikenal dengan keberaniannya melawan penjajahan Belanda dan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam.
Nama kecilnya adalah Muhammad Yusuf. Ia lahir di Istana Tallo, Gowa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626 atau dalam kalender Hijriah, 8 Syawal 1036 H.
Syekh Yusuf adalah putra dari Abdullah Khidhir, seorang bangsawan, dan Aminah I Tubiani Daeng Kunjung, putri dari Daengta Gallarang Moncong Loe. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, sejak kecil ia diajarkan hidup sederhana dan dididik dalam berbagai ajaran Islam, termasuk bahasa Arab, tauhid, fiqih, dan lain-lain.
Saat berusia 18 tahun, Syekh Yusuf dinikahkan dengan teman dekatnya yang merupakan putri dari Sultan Alauddin yang bernama I Sitti Daeng Nisanga. Tak lama setelah pernikahannya, atas saran guru-gurunya, Syekh Yusuf meninggalkan istrinya dan tanah kelahirannya untuk memperdalam ilmu agamanya dan melaksanakan haji.
Perhentian pertamanya adalah di Banten, di mana ia disambut dengan hangat oleh Sultan Abu al-Mufakhir Mahmud Abd al-Qadir, penguasa Banten saat itu. Selanjutnya, Syekh Yusuf melanjutkan perjalanan ke Aceh, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Taj al-'Alam Safiat al-Din Syah.
Dalam pencariannya untuk memperdalam ilmu agama, Syekh Yusuf juga mengunjungi berbagai negara, termasuk Syam (Syria) dan Istanbul (Turki). Ia akhirnya kembali ke Makkah dan menjadi pengajar di Masjid al-Haram selama beberapa tahun.
Di luar negeri Syekh Yusuf juga menguasai dan mahir dalam urusan kenegaraan khususnya di bidang taktik dan strategi perang. Sekembalinya ke tanah airnya, Syekh Yusuf tidak langsung pulang ke Makassar, tetapi terlebih dahulu ke Banten.
Di Banten, ia berhasil memperoleh pengaruh besar, diangkat sebagai mufti, dan menjadi penasihat kerajaan. Ia juga memimpin pertempuran melawan Kompeni Belanda di Banten dan kemudian meneruskan perang gerilya di Jawa Barat (1682-1683).
Syekh Yusuf lalu ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ceylon pada tahun 1684 selama 10 tahun. Selama di pengasingan, ia menulis 17 buku yang membahas berbagai aspek agama Islam, terutama tauhid dan tasawuf.
Karena masih melakukan kegiatan yang melawan kompeni secara terselubung, Syekh Yusuf kemudian dibuang ke Afrika Selatan (1694). Di Afrika Selatan, perjuangan beliau tetap dilanjutkan lewat pembinaan mental-spiritual yang mantap.
Syekh Yusuf kemudian menghembuskan nafasnya selang lima tahun kemudian tepatnya tahun 1699. Dia dimakamkan di atas sebuah bukit tempat pembuangannya di Faure yang juga disebut Macassar. Atas desakan raja Gowa, 5 tahun kemudian jenazahnya dibawa ke tanah tumpah darahnya dengan kapal laut de Spiegel.[9]
Semasa hidupnya, Syekh Yusuf dikenal sebagai pribadi yang sangat mengesankan. Meskipun memiliki latar belakang keluarga bangsawan, namun ia memilih jalan hidup yang sederhana dan penuh perjuangan.
"Kalau dia mau hidup enak, sebenarnya ngapain dia melawan, semua orang sudah percaya sama di kok. Dia sudah menikah dengan putri raja, dia juga di ceylon seperti itu, ngapain lagi, apa yang dia cari? Yang dia cari adalah makna hakiki daripada kemerdekaan, kemanusiaan yang dimilikinya. Dan itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari diri dan lingkungan kebudayaan, ke-bugis-an dan ke-Makassaran-nya," ujar Sejarawan Prof Dr Anhar Gonggong sebagai pembicara Syekh Yusuf di Seminar Internasional Belajar Prinsip dan Karakter Bugis-Makassar, Senin (2/9/2024).
Bagi Syekh Yusuf, meskipun dirinya ditangkap, namun ada satu hal yang tidak akan pernah mereka dapatkan dari dirinya, yaitu hati nurani.
"Hati nurani perlawanan saya, anda tidak akan pernah menangkap, dan itulah yang menjadi hal yang menyebabkan saya mampu bergerak di tengah-tengah situasi yang demikian keras, anda mau menangkap saya, anda mau membunuh saya, dan segala macam, tapi ada satu hal yang anda tidak bisa tangkap dalam diri saya, yaitu yang ada di sini (hati nurani)," tutur Anhar Gonggong.
Nilai itulah yang terus dibawa Syekh Yusuf dalam melakukan perlawanan dan menyebarkan ajarannya. Sebab menurutnya, makna kemerdekaan sesungguhnya adalah kemerdekaan hati.[6]
Jenderal M Jusuf, Panglima yang Mengayomi Prajuritnya
 Jenderal M Jusuf (Foto: Wikimedia Commons) Jenderal M Jusuf (Foto: Wikimedia Commons) |
Jenderal (purn) M Jusuf merupakan salah satu tokoh nasional asal Sulsel yang memiliki nama asli Andi Muhammad Jusuf Amir. Dia lahir di Kajuara, Kabupaten Bone pada 23 Juni 1928.
Jenderal M Jusuf merupakan keturunan bangsawan dari suku Bugis yang ditandai dengan gelar 'Andi' di depan namanya. Darah bangsawan itu didapat dari ayahnya yang disebut-sebut merupakan Raja Kajuara bernama Arung Kajuara.[1][2]
Akan tetapi, karena kerendahan hatinya M Jusuf melepas gelar bangsawannya pada 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi. Meski sudah tidak menggunakan gelar bangsawan, M Jusuf tetap menerapkan nilai-nilai Bugis dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai orang bersuku Bugis, Jenderal M Jusuf memegang teguh prinsip bahwa kehormatan dan harga diri di atas segala-galanya atau biasa disebut siri' na pacce.[3]
Selain itu, dia mengemban jabatan dan tugasnya dengan sifat jujur dan lurus atau masyarakat Bugis menyebutnya 'malempu'. Dia juga dikenal tertutup, tidak suka mengumbar-umbar cerita, dan merepotkan orang lain. Prinsip hidup ini disebut Jenderal M Jusuf dalam bahasa Bugis sebagai 'ampe', artinya adalah watak atau etika.
Selama berkarier, Jenderal Jusuf memiliki kiprah cemerlang baik di lingkungan Tentara Republik Indonesia (TNI) maupun sebagai petinggi di lembaga eksekutif. Oleh karena itu, namanya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa penting di Indonesia.
Dia merupakan salah satu tokoh di balik ditandatanganinya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menjadi awal peralihan kekuasaan Presiden Soekarno ke Soeharto. Jenderal Jusuf juga pernah memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang mengancam kedaulatan negara Indonesia. [1][4]
Usai menumpas pemberontakan DI/TII, M Jusuf ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian di beberapa periode pergantian kabinet di Indonesia. Karena mengemban jabatan itu, M Jusuf tidak menggunakan seragam militernya selama belasan tahun.
Akan tetapi, pada 29 Maret 1978 Jusuf kembali ke militer dan mencapai puncak kariernya setelah ditunjuk sebagai Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan RI. Selama menjabat, namanya melejit karena dikenal ramah, jujur, rendah hati, dan dermawan.
Ketenarannya pun sempat membuat Presiden Soeharto ketar-ketir karena kalah pamor. Sampai pada akhirnya, dia ditempatkan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada 1983-1988 dan 1988-1993. [1]
Setelah masa jabatannya berakhir, Jenderal M Jusuf berhijrah ke Makassar. Kemudian pada 8 September 2004 pukul 21.35, tokoh nasional ini meninggal pada usia 76 tahun karena penyakit yang sudah lama dideritanya. [2][4]
Bacharuddin Jusuf Habibie, Bapak Teknologi Indonesia yang Visioner
 BJ Habibie (Foto: Instagram @b.jhabibie) BJ Habibie (Foto: Instagram @b.jhabibie) |
Bacharuddin Jusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai BJ Habibie lahir di Parepare, 25 Juni 1936. Dia merupakan anak dari pasangan suami-istri Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA Tuti Marini Puspowardoyo.
Sejak kecil, Habibie menampakkan perilaku unik dan berbeda dari anak sebayanya. Habibie kecil lebih suka membaca buku di rumah sampai harus dibujuk oleh kakak-kakaknya agar mau bermain di luar.
Keunikannya itu juga terlihat ketika masih di taman kanak-kanak. Saat ditanya oleh gurunya tentang cita-citanya kelak, Habibie selalu mantap menjawab ingin menjadi seorang insinyur.[1]
Ketika beranjak dewasa, Habibie pun melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun, setahun berselang Habibie yang haus akan ilmu pengetahuan memutuskan berhenti dan melanjutkan pendidikannya di Jerman.[1][5]
BJ Habibie kemudian berangkat menuju Jerman Barat menumpang pesawat KLM (Royal Dutch Airlines). Itu merupakan pengalaman pertama Habibie menggunakan pesawat terbang.
Setelah sekian lama menuntut ilmu, pada 1960 Habibie akhirnya meraih gelar Diploma Ing yang setara dengan S1. Mulai dari sinilah karier Habibie dalam konstruksi pesawat terbang dimulai.
Pada 1965, dia menyelesaikan pendidikan doktornya dan meraih predikat 'sehr gut' atau sangat baik. Setelahnya, dia pun bekerja di Hamburger Flugzeugbau (HFB) di Hamburg. Selama bekerja, Habibie berhasil menunjukkan kepiawaiannya dengan menyelesaikan sejumlah persoalan yang sulit terpecahkan.
Salah satunya, persoalan terkait kestabilan konstruksi di bagian belakang pesawat F 28 yang saat itu dikembangkan sudah tiga tahun tidak selesai. Namun, di tangan Habibie persoalan itu selesai hanya dalam kurun waktu 6 bulan.
Kepandaian Habibie dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumit itu berkat kemampuannya identifikasinya yang luar biasa. Dia juga memiliki banyak ide dan mampu mentransformasikannya menjadi kenyataan.
Dengan kejeniusannya itu, dia dijuluki Mr Crack karena dapat merumuskan Teori Crack yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atap pesawat terbang dengan lebih presisi. Dengan rumus tersebut, Habibie memperoleh gelar kehormatan Guru Besar dari ITB dan Penghargaan Tinggi Ganesha Praja Manggala.[5]
Selain itu, pengakuan dari Lembaga internasional juga berdatangan dari berbagai negara seperti penghargaan bergengsi Edward Warner Award dan Award von Karman.[6]
Setelah sukses berkarier di Jerman, Habibie yang saat itu menduduki posisi Vice President dan Director of Applied Technology di perusahaan Jerman Messerschmitt Bolkow-Blohm (MBB) dipanggil pulang ke Indonesia. Dia dipanggil langsung oleh Presiden Soeharto karena kondisi Tanah Air di bidang ilmu dan teknologi jauh tertinggal.
BJ Habibie yang sejak dulu memang memiliki keinginan besar untuk membangun Indonesia menyatakan kesiapannya dan pulang ke Indonesia. Begitu pulang, Habibie meminta izin mendirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) terbang dan menjadi direktur utamanya.
Beroperasinya IPTN sekaligus menjadi pangkal kebangkitan teknologi tinggi Indonesia. Pengerjaan proyek ini dinilai menyedot banyak anggaran tapi menurut Habibie, proyek teknologi tinggi seperti ini akan menjadikan manusia-manusia dan produk berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman.
Kemudian pada 1998, Habibie menjadi wakil presiden dari Soeharto namun hanya berlangsung singkat. Ditahun yang sama, Soeharto lengser dari jabatannya dan digantikan oleh BJ Habibie sebagai presiden ke-3 Republik Indonesia.
Setelah 1 tahun 5 bulan menjabat, Habibie juga lengser dari kekuasaannya kemudian menjadi warga negara biasa yang bermukim di Jerman. Kemudian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, BJ Habibie mendirikan Habibie Center untuk memajukan proses modernisasi dan demokrasi di Indonesia.[7]
Segelintir kecemerlangan Habibie tersebut tak terlepas dari prinsip dan karakter Bugis-Makassar yang dipegangnya. Prinsip Bugis-Makassar yang dipegang Habibie dapat digambarkan dalam istilah 3B, yakni berilmu, beragama, dan berani.
"Jadi orang Bugis-Makassar itu harus berilmu, harus beragama tentunya, harus punya agama-kepercayaan, dan harus berani," ujar Putra pertama Habibie Ilham Akbar Habibie, dalam seminar bertajuk Ethos 4 Jusuf di Universitas Hasanuddin, Senin (2/9/2024).
"Dan kalau kita menerjemahkan dan menerapkan itu pada kehidupan bapak, bagi curriculum vitae-nya itu kalau memang demikian akan berdampak dan bermakna," sambungnya.
Sepanjang hidupnya, BJ Habibie tak henti-hentinya menghasilkan karya, pemikiran, dan gagasan yang menjadi warisan tak ternilai bagi generasi penerus bangsa. Pada 11 September 2019, Bapak Teknologi Indonesia yang jenius itu berpulang ke pangkuan Sang Khaliq.[8]
Jusuf Kalla, Sosok Pekerja Keras yang Berani dan Cerdas
 Jusuf Kalla (Foto: Muhammad Fida/detikcom) Jusuf Kalla (Foto: Muhammad Fida/detikcom) |
Jusuf Kalla adalah salah satu tokoh Bugis yang sangat inspiratif. Berawal dari memimpin perusahaan orang tuanya, Jusuf Kalla kemudian bertransformasi menjadi Wakil Presiden Indonesia yang membawa banyak perubahan dalam kepemimpinannya.
Kesuksesannya itu tidak terlepas dari prinsip hidup yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupannya. Pria yang memiliki nama lengkap Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla ini lahir pada 15 Mei 1942 di Watampone, Sulawesi Selatan.
Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya, ia mengikuti orang tuanya pindah ke Makassar. Sejak itulah ia diikutsertakan oleh orang tuanya dalam pertemuan bisnis dan akhirnya dipercaya memimpin perusahaan NV Hadji Kalla Trading Company pada tahun 1967.
Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang pesat hingga menjadi Kalla Group yang kini memiliki berbagai sektor industri, termasuk otomotif, transportasi, konstruksi, dan properti.
Selain fokus pada pengembangan bisnis, Jusuf Kalla juga terjun ke dunia politik sejak duduk di bangku kuliah. Ia menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 1965-1968 mewakili Sekber Golkar.
Kemampuannya dalam mengambil dua peran penting dalam di usia yang terbilang muda, menunjukkan bagaimana karakter Jusuf Kalla. Dalam budaya Bugis, nilai tersebut disebut 'pajjama' yang artinya pekerja keras.
Nama Jusuf Kalla kemudian semakin dikenal luas ketika ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah bergulirnya era reformasi, tepatnya ketika Presiden BJ Habibie digantikan oleh KH Abdurrahman Wahid.
Karier politik Jusuf Kalla pun semakin melejit hingga membawanya menjadi orang nomor dua di Indonesia. Dalam perannya sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla dikenal berani dan tidak takut menghadapi tantangan dan selalu mengambil sikap tegas demi kepentingan bangsa yang dalam budaya Bugis disebut 'magetteng'.
Salah satu contohnya adalah kebijakannya dalam rasionalisasi harga BBM, dengan alasan bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak kenaikan BBM.
Kecakapan diplomasi Jusuf Kalla juga membawa Indonesia ke posisi yang dihormati di kancah internasional. Keahliannya tersebut diperoleh dengan menerapkan diplomasi ala Bugis, yakni diplomasi tiga ujung.[3]
Selain berkiprah di dunia bisnis dan politik, Jusuf Kalla juga dikenal karena kontribusinya dalam bidang sosial. Melalui Yayasan Kalla dan Palang Merah Indonesia (PMI), ia telah banyak membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana.
Semangat 'sipakatau' yang berarti saling menghormati dan memanusiakan sesama, menjadi landasan bagi kepedulian beliau terhadap masyarakat.[6]
Referensi:
1. Buku berjudul "Empat Figur Jusuf Potret Pembelajaran Karakter" oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Buku berjudul "Jenderal-jenderal yang Mempengaruhi Sejarah Dunia" oleh Lukman Santoso Az.
3. Buku berjudul "JK Ensiklopedia" oleh Husain Abdullah dkk.
4. Jurnal Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan berjudul "Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dalam Kajian Sumber Sejarah Lisan 1950-1965".
5. Buku berjudul "Mr. Crack dari Parepare".
6. Seminar Nasional 4 Ethis 4 Jusuf, Prinsip dan Karakter Bugis-Makassar
7. Buku berjudul "Bacharuddin Jusuf Habibie" oleh Tasya Putri Hasanah
8. Buku berjudul "BJ Habibie dalam Kenangan Ragam Kesan dan Pengalaman Bersama Almarhum" oleh Wendy Aritenang dkk.
9. Buku Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Ulama Shufi, Pejuang Abad ke 17 dan Pahlawan Nasional
(urw/alk)



























































